Cerita Pendek (Cerpen) Stay
Rain In Shadow→ Salam para pengunjung setia, kali ini saya akan membagikan sebuah karya Cerpen yang ditulis oleh Esti Noor, yang berjudul Stay jadi penasarankan bagaimana ceritanya silakan baca selengkapnya di sini.
Stay
Karya Esti Noor
“Kumat lagi penyakit jiwanya?”
Terkedik bahuku ketika suara berat tersebut mengetuk pendengaran tanpa
dinyana. Febri yang tengah mengulum senyum tipis tengah memandang Belinda,
ketika aku menoleh ke kiri. Tak menjawab pertanyaan retoriknya, aku memilih
turut menerbitkan senyum sembari kembali memandang Belinda yang heboh dengan
lipstiknya di sana. Selalu begitu teman-temanku yang perempuan itu, akan sibuk
dengan kosmetik di jam istirahat seperti ini.
“Belajar caranya bersolek, dong.” Febri menyenggol lenganku dengan
sikutnya “Supaya mengerti bahagianya cewek.”
“Feb, bahagianya cewek itu bermacam-macam, OK? Stop nyuruh-nyuruh
aku kayak gitu.”
“Duh, yang sewot hanya karena disuruh dandan,” Febri mencibir. Terlihat
dari sudut mataku, cowok itu tengah bersidekap sembari menatapku penuh senyum
jail. “Kan biar cantik seperti Linda. Biar banyak cowok yang naksir.”
Aku memberinya tatapan tak bersahabat. “Ditaksir kamu aja udah cukup
merepotkan. Aku nggak mau menghabiskan masa SMA-ku dengan sesuatu yang
menyebalkan seperti itu.”
Febri memutus pandangan kami berdua dan bertopang dagu demi memandang
Belinda yang tengah bersolek di bangku guru bersama anak-anak perempuan
lainnya. Ada secercah senyum yang tak bisa kupahami maknanya terbit di sudut
bibir cowok ini. “Jangan begitu. Mana tahu besok aku sudah tidak menyukaimu
lagi. Hati manusia siapa yang tau.”
Berdebar jantungku, entah mengapa, ketika sekali lagi mendengar kalimat
sejenis itu keluar dari bibirnya yang tipis. Ada setitik rasa takut dalam hati
setiap kali Febri berkata demikian, seperti aku akan benar-benar menyesali
telah mengabaikannya selama ini.
Tawanya yang tiba-tiba membuatku terkesiap, tak sadar telah memandangnya
begitu lekat. Cowok berkacamata itu tengah asyik dengan gelaknya, lantas
tangannya mengusap wajahku, membuatku kesal.
“Tapi tenang aja.” Febri sekali lagi tersenyum, kali ini terlihat sangat
lembut. “Aku akan pamit terlebih dulu ketika tiba saatnya aku berpaling dari
kamu.”
Hati manusia siapa yang tahu.
Kalimatnya sukses menjadi sebuah kecamuk dalam pikiranku.
“Manusia memang begitu,” kataku, membalas senyumnya dengan sejenis senyum
sarkas. “Mudah berubah. Mana tahu, tiba saatnya kamu berpaling nanti, ternyata
adalah masa ketika aku mulai melihatmu. Mana tahu.”
Dan sekali lagi aku akan merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan.
Aku tersenyum miris dalam hati. Dia tak akan mengerti apa yang selama ini
kulewati, hingga dengan tega kuabaikan seluruh perasaannya yang tulus. Ada
seonggok perasaan yang tak bisa dengan tenang keluar dari dalam jiwa, terlalu
riskan keluar dari atap perlindungan, terlalu cemas akan pulang penuh luka,
hingga pada akhirnya hanya diam di dalam sana, menolak membukakan jalan
teruntuk siapapun.
“Haduh,” Febri mengeluh, menjatuhkan kepala ke atas meja. Aku
memandangnya datar. “Kamu ini sebenarnya mau nge-PHP aku sampai kapan, Han?
Selalu pas aku bilang begitu, kamu ngasih sinyal seakan suatu hari akan
membalas perasaanku.”
“Kamu sendiri yang bilang, mana tahu.” Aku mengedikkan bahu ringan, tak
acuh akan keluhannya. Kepalaku lantas mengedik pada Belinda yang baru saja
memanggilku, memintaku bergabung bersama kumpulannya yang gemar bersolek. Aku
meringis, menolak ajakan cewek blaster Belanda itu.
Terdengar suara deritan kursi di sebelah kiri. Febri sudah berdiri dan
keluar dari bangku Belinda, menjauh dari sisiku. Aku mendongak demi memandang
wajah kerasnya yang berdiri menjulang di samping bangku.
Bukannya bodoh aku untuk menyadari kemarahannya. Tapi aku pun tak bisa
melakukan apapun, bahkan pada diriku sendiri.
“Sebenarnya aku sudah sangat bosan,” Febri berujar. Keningnya mengerut,
seolah kalimatnya barusan membuat tekanan tersendiri baginya. “Tapi kemudian
aku bertanya-tanya, sedangkal apa rasa sukaku padamu, hingga mudah aku
berpaling. Jangan sampai kemudian suatu hari aku menemukan jawabannya dari
ketidakpedulianmu ini, Han.”
“Jangan bingung begitu,” aku meniru nada bicaranya, sengaja memancing
kemarahannya. Ingin aku sekali lagi melihat urat-urat itu keluar. “Mana tahu
kamu memang sudah lama menemukan jawabnya. Bertanya-tanya lah, kenapa kamu
masih bertahan ketika sudah menemukan jawaban?”
“Karena aku bukan Haikal!”
***
“Kamu beneran nggak mau nyoba dulu sama Febri?”
Terlepas dari adiksinya terhadap seluruh jenis kosmetika, Belinda adalah
seorang sahabat yang begitu pengertian. Dia tengah menatapku penuh kecemasan,
padahal berkali-kali kukatakan padanya bahwa aku baik. Hanya karena aku tertawa
atas candaannya, dia begitu saja mengira aku kenapa-napa. Bukannya ingin
menyalahkan asumsinya, aku memang sedikit tidak baik.
“Kamu sendiri yang bilang kalau setiap orang itu berbeda,” Belinda tetap
pada pendiriannya untuk membahas topik yang sebenarnya enggan untuk kubahas
berulang bersamanya. Dia jelas-jelas tahu jawabanku. “kalau nggak semua cerita
yang serupa berakhir dengan jalan yang sama. Coba dulu lah, Hani. Febri itu
cowok baik-baik. Sudah berapa lama sih kita kenal dia? Dia sudah naksir kamu
sebelum kejadian kamu pacaran sama Haikal dan sekarang terpuruk gini. Dia tetap
sama perasaannya. Apa lagi yang bikin kamu ragu? Febri jelas bukan cowok
semacam Haikal.”
Kami tengah duduk bersebelahan di halte di seberang sekolah, menanti angkutan
umum menuju jalur rumah kami tiba. Biasanya aku akan membahas hal-hal
menyenangkan bersama Belinda, seperti bagaimana tingkah konyol Raditya Dika di
Malam Minggu Miko. Tapi sekarang Belinda ngotot membahas pembicaraanku dengan
Febri di kelas tadi. Rupanya cewek itu mendengar apa-apa saja yang tadi sempat
kubicarakan dengan Febri.
“Dengar ya. Mungkin kamu begini karena Febri seolah masih akan terus suka
sama kamu, makanya kamu sesantai ini membiarkan Febri tanpa kepastian begitu.
Tapi aku nggak mau lihat kamu menyesal ketika suatu saat Febri benar-benar
melihat cewek lain. Kamu nggak akan mau merasakan betapa tersiksanya batin yang
begitu ingin waktu kembali pada masa yang baik-baik saja.”
Aku memberi Belinda seutas senyum.
Tanganku menepuk pundaknya pelan ketika mobil kuning angkutan umum tiba dan
menepi ke bahu jalan. “Ayo pulang. Angkotnya dateng tuh.”
***
Ada masa di mana aku merasa hidup dalam dunia yang sebelumnya hanya
berani aku impikan. Masa di mana semua berjalan begitu sempurna, berjalan sesuai
dengan keinginan. Menjalin hubungan dengan cowok yang disukai adalah apa yang
bisa kuimpikan.
Aku menyukai Haikal, cowok kelas sebelah yang berwajah manis khas remaja
bumi pertiwi. Menyukainya selama kurang lebih empat bulan, lalu suatu hari ia
mengajakku berpacaran di hari yang cerah. Seperti mimpi di siang bolong memang,
tapi Belinda memberitahuku bahwa aku sudah jadi pacar Haikal Birawan. Hari itu
rupanya bukan sekadar mimpi.
Tapi tak sampai sebulan, kutemukan Haikal tengah tertawa bersama banyak
gadis. Baru lah aku sadar bahwa Haikal Birawan bukan lah tipe pemuda yang bisa
tertawa bersama seorang gadis saja. Perasaanku terkhianati oleh cowok itu.
Rasanya begitu sakit ketika cinta pertama tak berjalan semulus kisah buku
cerita.
Dan ini lah aku yang sekarang, Hani Ayunda yang tak lagi bisa meletakkan
kepercayaan pada pemuda mana pun.
“Ada Tante Fira, Nda.” Tanpa basa-basi Mama tiba-tiba menyembulkan diri
dari balik tirai kamarku yang tertutup. Wajahnya riang, seperti biasa. “Ada
anaknya juga. Katanya dia sesekolah sama kamu loh.”
Sialan.
Tanpa sadar aku begitu saja bangkit berdiri dari posisi terlentangku di
atas kasur ketika mendengar ucapan Mama.
Anak Tante Fira tak lain adalah Haikal.
Mama tak pernah tahu bahwa aku pernah berpacaran. Keluargaku tak tahu aku
pernah menjalin hubungan dengan cowok mana pun. Bukan bermaksud tertutup, hanya
saja, pada dasarnya aku memang belum diijinkan untuk hal-hal seperti itu. Masih
terlalu dini, kata Papa.
Benar saja. Tiba di ruang tamu, yang kudapati adalah seorang cowok tinggi
berisi tengah duduk di sebelah wanita berhijab yang sedang tersenyum menyambut
kedatanganku di sisi Mama.
Tante Fira tak banyak berkata, hanya mengulurkan tangan ke arahku,
memintaku untuk mendekat padanya. Pada akhirnya, aku duduk di sebelahnya, tepat
di tengah ibu dan anak ini.
“Assalamualaikum, mantan calon menantu Tante kkhh,” Tante Fira berbisik
padaku, membuatku nyaris terlonjak.
Cukup sering dulu Haikal membawaku main ke rumahnya. Tak ayal, aku
bertemu Tante Fira yang notabene juga merupakan teman masa SMP Mama. Sekarang,
dipertemukan dengan Tante Fira setelah hubunganku dan Haikal kandas, rasanya
sangat risih. Tante Fira juga tak kusangka akan menyinggung masa-masa itu
dengan sapaannya.
“Haikal ini IPA 4 ya?” suara Mama membuatku menoleh ke depan. Mama sedang
duduk seorang diri di sofa yang berjarak meja oval di hadapanku. “Kayaknya
bangunan kelasnya sebelahan sama kelas Unda. Kamu IPA 3 toh ya, Nda? Seingat
Mama pas rapat kemarin, kelasnya berjajar sebelahan mulai dari IPA 1 sampai 5.
Benar?”
Kudapati Haikal tersenyum sopan dan membalas ucapan Mama, “Iya, Tan.
Kelasku sebelahan sama kelas Ayunda. Sering kok kami ketemu, kadang-kadang juga
main ke kantin bareng.”
Iya, pas pacaran dulu ya, Kal.
Batinku memanas mendengar ucapan manisnya.
“Akrab dong,” kata Mama lagi. Wajahnya santai, tanpa mau menerka-nerka
apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Mama bahkan kini sedang menyeruput
tehnya dan mulai berbincang dengan Tante Fira.
“Nda,” Semenjak pacaran, Haikal juga jadi ikut-ikutan memanggilku dengan
nama kecilku. Aku menoleh ketika dia lirih memanggilku. Pandangannya masih sama
seperti dulu, masih tatapan seorang Haikal Birawan yang membuatku menyukainya.
“Tadi aku ketemuan sama Febri.”
***
Baca Juga : (Cerita Pendek Karya Esti Noor; Kopi Hitam)
“Mungkin Bunda tau kalau kita berpisah dengan nggak baik.” Haikal
menunduk, tangannya mengusap tengkuk, sepertinya terlihat sangat canggung.
Setelah cukup lama terdiam, akhirnya dia mendongak dan kembali memandangku.
“Makanya dia sekalian ngajakin aku ke rumahmu.”
Kami sedang berada di pos siskamling di seberang rumah. Bangunan ini
terbuat dari bambu dan beratap daun kering, entahlah aku tak tahu namanya.
Kakiku terjuntai karena ketinggian tempat duduk yang lumayan.
“Nda, kamu dengar aku kan?”
Biasanya aku memang akan duduk di sini ketika sore hari, seperti
sekarang, entah untuk mengadem atau sekadar memerhatikan anak-anak kecil yang
bermain sepeda. Angin sore biasanya sangat nyaman, namun kali ini, sama seperti
hatiku, alam turut membeku.
“Nda, aku minta maaf.”
Ah, akhirnya kudengar juga kalimat itu dari bibirnya. Rasanya seperti
oase di tengah kering Sahara. Tapi apalah arti maaf kalau semua telah terberai
menjadi jutaan keping tak bermakna?
“Nda.”
“Terima kasih sudah meminta maaf,” akhirnya aku bersuara. Kupandang
matanya yang entah mengapa penuh kegetiran. “Seenggaknya nanti kita nggak perlu
berlagak temenan di depan Tante Fira. Toh, kita memang udah baik-baik aja kan
sekarang.”
“Kamu tipe cewek yang susah buat diterka, Nda.” Haikal rupanya masih
tidak canggung untuk berpandangan lama denganku, sementara aku di sini sudah
ketar-ketir. “Kupikir kamu nerima aku dulu hanya karena iseng. Sejak hari di
mana kamu bilang baik-baik aja ketika aku bilang akan pergi dengan Amanda,
kupikir kamu emang nggak serius sama hubungan kita. Biar lah kamu pikir aku cowok
sensitif, tapi yang perlu kamu tau, aku bukan tipe cowok yang bisa tertawa
dengan banyak cewek. Hari itu hanya bentuk pembalasan perasaan kesalku.”
“Amanda adalah teman kamu, apa yang harus aku cemaskan dengan itu, Kal?”
Berikutnya aku mendesah lelah. “Udahlah, percuma juga dibahas, udah lewat.”
Baik aku maupun Haikal terdiam untuk beberapa saat. Aku memilih membuang
pandangan pada satu-dua anak kecil yang melintas di hadapan dengan sepeda
mereka.
“Kesalahan kita hanya karena nggak saling terbuka satu sama lain. Nda!
Aku mau kamu dengerin aku dengan serius kali ini!”
Aku cukup kaget ketika Haikal mengeraskan suara, dia terdengar sangat
tegas, membuatku menoleh padanya.
“Nggak ada orang jahat kalau kita menemukan cara menaklukannya. Kegagalan
kemarin bukan karena aku cowok yang nggak bisa kamu percaya, bukan cowok yang
mudah berkhianat, dan kalau pun semisal aku seperti itu, jangan hanya karena
satu orang lalu kamu memukul rata penilaian tersebut pada semua cowok.” Ini
jelas bukan Haikal yang kukenal. Haikal Birawan adalah cowok santai yang tak
mau ambil pusing dengan kejadian apapun. Kupikir ini ada hubungannya dengan
pertemuannya dengan Febri yang sempat ia singgung tadi. “Setiap orang berbeda,
Nda. Jangan kamu menutup diri begini hanya karena aku. Kamu tau bahwa pada
akhirnya ini hanya kesalahpahaman.”
“Jadi Febri minta kamu untuk membicarakan ini denganku?”
Kepalanya menggeleng. “Dia meminta aku mengembalikan hatimu yang katanya
masih tertinggal padaku.”
***
Baca Juga : (Cerita Pendek Karya Esti Noor; 07)
“Nggak sih, tadi malem aku ngemilin kerupuk. Kebetulan Ibu abis nyetok
kecap di kulkas.”
Rasanya bukannya bodoh ketika aku tidak menyukai sosok di hadapanku ini.
Tingkahnya kelewat konyol, menyebalkan kadang-kadang. Tawanya seolah tak
berurat malu, menggelegar keras. Hanya satu yang bisa dia banggakan, itu pun
tak bisa dengan cara yang berlebihan; wajahnya yang manis. Oh, dia juga pandai
Matematika, meski begitu payah di Bahasa Inggris.
Dulu, aku memang sempat mendengar kasak-kusuk bahwa dirinya menyukaiku,
jauh sebelum akhirnya aku berpacaran dengan Haikal. Siapa yang menyangka,
seminggu setelah aku putus, cowok itu bilang dengan mulutnya sendiri bahwa dia
masih suka padaku.
Aku tak mengenalnya dengan baik sebelum pengakuannya hari itu. Yang
kutau, bahwa namanya Febri Aris. Nomor absen 5, dan hobi sepak bola.
“Feb,” aku menginterupsi ocehannya yang ngalur-ngidul. Saat ini kelas
sedang istirahat. “Coba deh latihan nembak aku, kali aja kamu lupa.”
Keningnya sontak mengerut. “Memangnya kalau kutembak lagi, bakalan
diterima?”
Aku menggeleng santai. “Cuma biar kamu nggak lupa caranya nembak. Harus
sering-sering latihan.”
“Oke.” Dia mengangguk. “Han, ayok pacaran sama aku.”
“Ayo.”
TAMAT


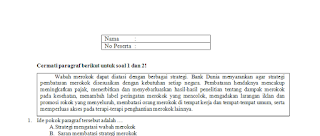



Tidak ada komentar: